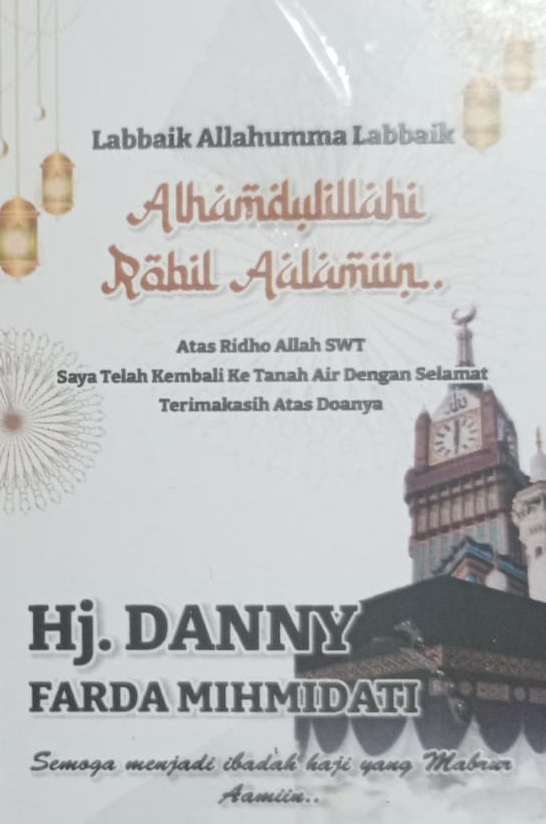Saya tidak pernah berencana pergi malam itu. Tapi banyak hal dalam hidup memang tidak menunggu rencana. Kita bisa menuliskan peta perjalanan, tapi Tuhan sering kali melipat petanya dan menuntun langkah kita lewat arah yang lebih pelan—lebih lembut. Kepergian saya ke rumah itu bukan keputusan saya. Ada angin tipis yang mendorong dari balik takdir. Angin yang pelan, tapi cukup kuat untuk membuat saya berdiri dan melangkah keluar.
Rumah itu tidak beralamat di kenangan saya. Tapi aneh, sejak saya duduk dan mencicipi seteguk air Zamzam yang disuguhkan, rumah itu seperti memanggil nama saya yang paling sunyi. Tidak ada plakat nama di dinding. Tidak ada tanda bahwa rumah ini adalah tempat sakral. Tapi saya merasa, di malam itu, rumah ini menjadi semacam musala kecil dalam jiwa saya. Ada karpet bermotif Timur Tengah yang membuat saya duduk lebih pelan, lebih hati-hati, seperti hendak membaca ayat yang belum diberi harakat.
Dan di hadapan saya: perempuan yang tidak terlalu tua, tidak pula terlalu muda. Namanya Hj. Danny Fardah Mihmidati. Gamis krem, kacamata tipis, dan senyum yang tidak selesai. Ia menyambut saya bukan dengan basa-basi, tapi dengan keheningan yang hangat. Seperti seseorang yang telah banyak mendengar kabar dari langit, dan kini memilih diam agar tidak mengacaukan makna.
Ia dari kloter SUB-44—rombongan haji yang disebut-sebut sebagai “kloter tertunda”. Tapi ia mengucapkan kata “tertunda” bukan dengan nada kecewa. Ia menyebutnya seperti orang menyebut tanggal lahir: netral. Lalu ia berkata, “Tertunda, Mas. Tapi ternyata yang tertunda itu bukan hanya kepulangan. Tapi juga kesedihan.”
Saya mengulang kalimat itu dalam hati. Saya kunyah perlahan seperti ayat yang belum saya hafal. Kalimat itu masuk ke dalam diri saya seperti kabut—diam, tapi membuat pandangan saya berubah.
Lalu ia bercerita. Tentang pengumuman yang datang tiba-tiba. Tentang tangis yang terdengar di koridor hotel Jeddah. Tentang para jamaah yang mendadak kehilangan arah—bukan karena takut tersesat, tapi karena merasa sudah waktunya pulang. Tapi Tuhan belum membuka pintunya.
Namun seperti biasa, Tuhan punya cara membungkus rahmat dengan kejutan. Hotel yang diberikan bukan hotel biasa. Bukan hanya karena bintang lima, bukan karena menu sarapan atau lift yang berzikir. Tapi karena kamar itu, bagi sebagian jamaah, menjadi tempat pertama mereka mengenal sunyi yang tidak menyakitkan.
“Awalnya kami sedih,” kata Danny. “Tapi begitu masuk kamar hotel itu, kami tertawa seperti anak-anak yang baru tahu rasa cokelat.”
Saya nyaris tertawa. Tapi tawa saya nyangkut di tenggorokan. Saya ingat betapa sering saya marah pada rencana kecil yang tidak berjalan. Betapa saya tidak sabar bahkan untuk antre lima menit. Betapa saya mengukur hidup dengan jadwal, padahal hidup sendiri sering kali datang tanpa waktu.
Danny tidak sedang menggambarkan kemewahan. Ia sedang menunjukkan sisi Tuhan yang tidak kita hafal. Bahwa kadang, hadiah-Nya datang terlambat—karena kita belum siap membukanya.
Lalu ia berkata lagi, pelan. “Mas, kadang kita tidak perlu terburu-buru pulang. Karena Tuhan juga tidak selalu terburu-buru memberi. Tapi Ia pasti memberi. Itu pasti.”
Saya menunduk. Saya hirup aroma teh yang disuguhkan. Teh itu tidak terlalu manis, tapi seperti mengandung kejujuran yang tidak kita temukan di mimbar-mimbar. Saya merasa sedang berbicara dengan seseorang yang sudah selesai dengan ambisi. Yang tidak meminta apa-apa lagi, kecuali satu: pulang dalam keadaan arah masih menghadap-Nya.
Saya bertanya, “Apa doa Ibu ketika di Multazam?”
Ia tersenyum kecil. Tapi saya tahu, senyum itu datang dari tempat yang dalam.
“Saya tidak berani berdoa banyak-banyak. Takut tidak kuat menerima,” jawabnya.
Kalimat itu menghantam saya seperti denting terakhir sebelum azan. Saya mendadak tidak ingin bertanya lagi. Tapi dia melanjutkan.
“Saya hanya bilang, ‘Ya Allah, saya terima apa pun. Asal Engkau tetap jadi arah saya pulang.’”
Dan malam itu, saya merasa bukan sedang mendengar cerita haji. Tapi sedang diajak menyaksikan satu jiwa yang telah selesai dengan ingin. Seorang manusia yang memilih menjadi peng-amin dalam doa-doa orang lain.
Kalau ada spiritualitas yang paling sunyi, itulah dia. Tidak menjadi pusat, tidak meminta jadi istimewa. Cukup menjadi gema kecil. Cukup menjadi suara “amin” yang lirih di ujung doa orang-orang yang masih punya banyak permintaan. Dalam diam saya, saya tahu: orang-orang seperti Danny bukan hanya naik haji secara fisik. Tapi hatinya sudah menyentuh maqam pasrah.
Saya lalu teringat Mina. Tahun lalu. Saat saya masih menjadi ketua kloter. Malam-malam tanpa tidur. Jamaah hilang arah. Makanan yang dibagi dengan tangan gemetar karena lelah. Tapi yang paling berat bukanlah mengatur barisan. Yang paling berat adalah menjaga agar hati tetap tidak kehilangan arah. Sebab haji, pada akhirnya, adalah perjalanan yang sangat pribadi.
Saya pulang malam itu dengan motor tua. Jalan sepi. Tapi di kepala saya, Tuhan sedang bicara. Bukan dengan suara, tapi dengan ingatan yang dilempar satu-satu. Dan saya sadar: malam itu bukan penundaan. Tapi perpanjangan waktu bagi hati saya untuk mendengar.
Saya ingat kolam renang di hotel itu. Kolam yang jernih, bersih, menggoda. Tapi para jamaah memilih tidak menyentuhnya, karena menjaga wudhu. Lalu saya membandingkan dengan diri saya sendiri—dan dengan kota ini. Kota yang penuh orang berenang dalam kesalahan, tapi tetap mengenakan pakaian takwa di luar tubuhnya.
Danny tidak sedang mengajak saya iri. Ia sedang berkata: bahwa dalam spiritualitas, mewah itu bukan kamar hotel. Tapi ketenangan yang tidak bisa dibeli. Dan keikhlasan, jika ditulis dalam satu kata, mungkin adalah: amin.
Amin yang paling dalam. Amin yang tidak berteriak. Amin yang tidak dipajang di status. Amin yang dibisikkan pelan di ujung malam, setelah semua keinginan ditinggalkan.
Dan saya merasa, malam itu Tuhan menyewa satu ruang dalam hati saya. Sebuah kamar kecil yang tanpa kasur empuk, tapi ada tikar doa. Tanpa AC, tapi cukup dengan sejuknya pasrah. Saya tidur malam itu bukan di atas ranjang, tapi di atas perasaan baru: bahwa diam juga bisa menjadi cara untuk menyembah.
Saya tutup malam itu dengan satu kata yang sejak kecil saya ucapkan tanpa berpikir. Tapi malam ini, saya ucapkan dengan air mata kecil yang tidak tumpah:
Amin.

Penulis : Syafaat