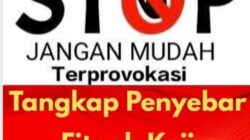Oleh : Joko Wiyono, SH.
Penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah masalah yang tak kunjung selesai, menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang sangat besar. Dalam upaya menanggulangi persoalan ini, pemerintah telah mengatur rehabilitasi sebagai pendekatan yang lebih manusiawi daripada penahanan di penjara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, meskipun telah ada dasar hukum yang jelas, pelaksanaan rehabilitasi masih perlu evaluasi, terutama terkait mekanisme dan prosedur asesmen terpadu yang seharusnya menjadi kunci keberhasilan pemulihan penyalahguna narkoba.
Salah satu landasan kebijakan rehabilitasi adalah penilaian antara paradigma kesehatan dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, penyalahguna narkoba yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika seharusnya diberikan rehabilitasi, bukan hukuman penjara. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini seringkali terdistorsi oleh faktor-faktor penegakan hukum. Banyak penyalahguna narkoba yang justru dipenjara, tanpa pertimbangan apakah mereka terlibat dalam peredaran narkoba atau hanya sebagai pengguna yang perlu mendapatkan pemulihan.
Penting untuk mencatat bahwa tingginya jumlah narapidana yang dipenjara karena kasus narkoba seharusnya menjadi bahan refleksi bagi para penegak hukum dan pembuat kebijakan. Apakah keputusan untuk memenjarakan mereka sudah tepat? Apakah mereka semua benar-benar terlibat dalam peredaran narkoba atau hanya sekadar penyalahguna yang membutuhkan rehabilitasi? Ini adalah pertanyaan yang mendasar dalam mengevaluasi efektivitas pendekatan hukum yang ada saat ini.
Untuk memperoleh rehabilitasi, penyalahguna narkoba harus menjalani prosedur asesmen terpadu yang melibatkan Tim Asesmen yang terdiri dari tim medis dan tim hukum. Tim medis bertugas untuk menilai kondisi fisik dan psikologis, sementara tim hukum bertanggung jawab memastikan apakah penyalahguna juga terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Meskipun prosedur ini bertujuan untuk memisahkan penyalahguna yang membutuhkan rehabilitasi dari mereka yang terlibat dalam peredaran narkotika, pada kenyataannya, sistem ini rentan disalahgunakan.
Oknum-oknum dalam Tim Hukum berpotensi memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan transaksi ilegal yang dapat mengarah pada praktik “perdagangan” rehabilitasi. Hal ini tentu sangat merugikan para penyalahguna narkoba yang seharusnya menerima hak mereka untuk dipulihkan melalui jalur medis, bukan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi oleh segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, masih terdapat masalah besar dalam pendekatan yang terlalu sempit pada asesmen terpadu. Asesmen saat ini lebih menekankan pada aspek medis dan hukum tanpa mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang juga sangat memengaruhi kondisi penyalahguna narkoba. Padahal, ketergantungan narkoba sering kali berkaitan erat dengan masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, pengucilan, atau kurangnya dukungan keluarga.
Rehabilitasi seharusnya tidak hanya berfokus pada terapi medis, tetapi juga harus mempertimbangkan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, penting untuk menambahkan komponen analisis sosial dan ekonomi dalam asesmen terpadu agar program rehabilitasi lebih komprehensif dan menyentuh akar permasalahan. Dalam konteks ini, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia dapat menjadi contoh yang baik. Di sana, proses asesmen terhadap penyalahguna narkoba dilakukan dengan cara yang jauh lebih holistik, menggabungkan evaluasi aspek kriminalitas, kondisi ketergantungan, hingga faktor psikologis dan sosial pengguna.
Penerapan asesmen terpadu di Indonesia, meskipun telah ada sejak lama, sistem yang ada lebih fokus pada aspek hukum dan medis, sementara faktor sosial dan ekonomi seringkali terabaikan. Jika kita melihat pada contoh negara-negara lain, pendekatan yang lebih komprehensif akan sangat membantu meningkatkan kualitas rehabilitasi dan mengurangi potensi penyalahgunaan dalam sistem ini.
Sebagai langkah perbaikan, penting untuk memperkuat integritas Tim Asesmen Terpadu. Tim medis harus diberikan peran yang lebih dominan, dengan tambahan analis sosial dan ekonomi yang dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi penyalahguna narkoba. Selain itu, asesmen harus dipandang sebagai hak individu, bukan hanya sebagai prosedur yang didorong oleh kepentingan hukum semata.
Pengawasan terhadap lembaga rehabilitasi juga harus diperketat, baik secara internal maupun eksternal, untuk menghindari penyalahgunaan dana (Bantuan pemerintah, Hibah, dan biaya rehabilitasi), dan praktik korupsi. Keterlibatan keluarga dan masyarakat juga perlu diperkuat agar peserta rehabilitasi merasa didukung dalam proses pemulihan mereka.
Rehabilitasi penyalahguna narkoba di Indonesia harus kembali kepada tujuan utamanya, yakni memulihkan individu agar bisa kembali berfungsi dalam masyarakat dengan sehat, baik fisik maupun mental. Hal ini hanya bisa tercapai jika sistem yang ada dijalankan dengan transparansi, profesionalisme, dan pendekatan yang lebih holistik. Pemerintah, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat perlu bekerja sama menciptakan ekosistem yang mendukung pemulihan, bukan malah memperburuk masalah dengan praktik-praktik yang menyimpang.