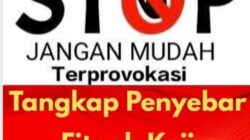Polemik pertambangan Galian C di Banyuwangi telah terjadi sejak dulu. Saat ini, dalam kurun waktu 2024 -pertengahan 2025, semakin terang-terangan eksploitasi lahan yang mestinya dilindungi terus terjadi, di kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pelanggaran ini tak hanya soal lingkungan, tapi mencerminkan rapuhnya tata kelola ruang, lemahnya pengawasan, dan adanya potensi pembiaran sistematis oleh pihak berwenang.
Secara normatif, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas PU CKPP sudah menjalankan tugasnya, menginformasikan permohonan izin perusahaan tambang dilahan LSD/LP2B, berdasar Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2024 serta bertentangan dengan regulasi nasional seperti UU 41/2009, Perpres 59/2019, hingga Permen ATR/BPN 2/2024. Tapi realitas di lapangan sungguh berbeda: tambang tetap beroperasi dengan leluasa. Ironisnya ESDM Provinsi Jawa Timur justru membenarkan bahwa pengajuan wilayah peta adalah wilayah pertambangan.
Kita menyaksikan bagaimana tata ruang daerah seolah hanya menjadi formalitas administratif. Padahal, menurut Pasal 35 UU Minerba (UU 3/2020), kesesuaian tata ruang adalah syarat mutlak dalam proses perizinan pertambangan. Jika kesesuaian ruang diabaikan, maka seluruh izin yang dikeluarkan berpotensi cacat hukum dan bisa dikenakan sanksi administratif, bahkan pidana, apabila berdampak pada kerusakan lingkungan atau konflik sosial.
Kegagalan dalam pengawasan ini memunculkan berbagai persoalan substansial:l, diantaranya :
Kerusakan lingkungan, terutama pada Daerah Aliran Sungai (DAS), lereng perbukitan, dan kawasan hutan lindung.
Potensi hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat banyaknya tambang yang tidak memiliki legalitas lengkap.
Konflik horizontal dan vertikal, antara warga dengan pengelola tambang, serta antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Saya yakin, berulang kali dilakukan audit perijinan dan pengawasan pertambangan, tetapi Tim Terpadu Pengawasan Tambang Banyuwangi sering tak berdaya di lapangan. Mereka menghadapi tekanan sosial dari pihak pengelola tambang dan pemilik truk pasir yang menolak penertiban, dengan lakukan deminstrasi besar. Kondisi ini menjadi bukti bahwa aparat pemerintah, baik di daerah maupun provinsi, dapat dikatakan gagal hadir sebagai pelindung kepentingan publik dan lingkungan.
Maka, ada beberapa langkah konkret dan strategis yang mendesak dilakukan:
Penegakan hukum secara tegas terhadap seluruh kegiatan tambang yang melanggar aturan, termasuk mencabut izin dan menindak secara pidana jika ditemukan unsur perusakan lingkungan atau pemalsuan dokumen.
Moratorium penerbitan izin baru sampai ada evaluasi menyeluruh terhadap kesesuaian tata ruang dan dampak sosial-lingkungan.
Reformasi kelembagaan dan regulasi pengawasan, termasuk penguatan peran daerah dalam kontrol ruang dan pertambangan,.atau bahkan di buatan BUMD Banyuwangi khusus pertambangan.
Pelibatan masyarakat sipil dan media dalam pengawasan partisipatif agar pengawasan tidak hanya elitis dan birokratis.
Tata ruang bukan sekadar dokumen teknis, tapi refleksi dari visi masa depan daerah. Jika aturan ruang hanya jadi pelengkap birokrasi, maka kita sedang menciptakan fondasi krisis jangka panjang. Tidak hanya ekologi yang rusak, tapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Sudah saatnya Banyuwangi bangkit sebagai daerah yang taat hukum, berdaulat atas ruangnya sendiri, dan berpihak pada kepentingan rakyat dan kelestarian alam. Jika tidak, kita hanya tinggal menunggu waktu sampai konflik horizontal, degradasi lingkungan menjadi warisan yang tak bisa lagi diperbaiki oleh generasi mendatang.
Opini ini ditulis sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis tata kelola pertambangan di Banyuwangi. Semoga menjadi bahan refleksi dan dorongan perubahan yang nyata.

Oleh : Joko Wiyono