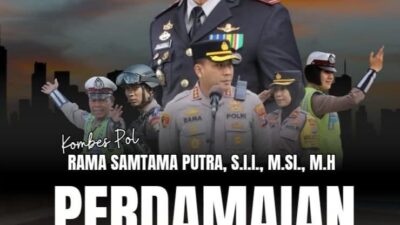Oleh : Syafaat (Ketua Lentera Sastra Banyuwangi)
Malam penutupan Festival Banyuwangi Tempo Dulu adalah malam yang penuh bayangan. Lampu-lampu panggung menyala seperti kunang-kunang yang terjebak di jaring raksasa, sementara angin dari Selat Bali membawa aroma laut yang samar-samar menyusup di antara kain batik Gajah Oling, kebaya, dan udeng yang dikenakan para penonton, orang-orang berdiri rapat, sebagian duduk di kursi undangan yang berjejer rapi, sebagian lagi bersila di tikar seadanya, dan sisanya sibuk mencari sudut paling pas untuk menyaksikan pertunjukan.
Ada yang menyalakan kamera kecil, ada yang menempelkan mata ke layar telepon genggam, berharap gambar bergerak itu kelak bisa disimpan dan dibagikan ulang, tetapi ada juga yang sekadar duduk diam, memandang, membiarkan malam menanamkan dirinya ke dalam ingatan.
Saya ada di sana, duduk di deretan undangan, di antara pejabat, seniman, dan warga yang datang dengan penuh rasa ingin tahu, saya merasa seperti sedang mencari sesuatu di bukan sekadar hiburan, saya ingin meraih sepotong makna dari panggung yang malam itu menampilkan tradisi pernikahan khas Banyuwangi: Mupus Braen Blambangan.
Saya tidak pernah bisa menolak undangan yang berkaitan dengan tradisi, barangkali karena saya lahir di tanah ini, tanah yang penuh percampuran, tanah yang diceritakan leluhur dengan cara berlapis-lapis, ada sejarah migrasi, ada riwayat perdagangan, ada kisah pelayaran. Namun, di balik semua itu, selalu ada satu rasa yang menempel pada saya: rasa seperti orang asing di rumah sendiri.
Saya teringat masa kecil, di sekolah dasar, teman-teman sering memanggil saya wong jowo kulon di sebutan itu terdengar sederhana, tetapi ia membawa garis pemisah yang tidak terlihat, saya bukan suku Osing di saya anak Jawa, lahir dari keluarga Mataraman yang datang dari barat, dari Tulungagung, Jogjakarta Kediri, atau mungkin lebih jauh lagi, kata itu melekat begitu lama, membuat saya sering merasa hanya sedang singgah, meski akte kelahiran saya jelas ditulis: lahir di Banyuwangi.
Namun malam itu, ketika gamelan ditabuh dengan ritme yang memanggil, ketika pengantin Mupus Braen memasuki panggung dengan segala riasan penuh makna, saya merasa dipanggil pulang, seakan ada meja besar terbentang, meja warisan leluhur, tempat semua orang Banyuwangi boleh duduk: Osing, Jawa, Madura, Bali, Arab, Cina, Bugis, tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi garis. Yang tersisa hanyalah rasa memiliki bersama, budaya ini milik kita, semua suku yang ada di bumi Blambangan.
Dan cinta, rupanya, adalah bahasa yang membuat semua pintu terbuka, Mupus Braen. Saya baru benar-benar mengerti artinya malam itu, mupus berasal dari kata pupus, daun muda di pucuk pohon: rapuh, hijau, penuh harapan. Braen berarti indah, menawan, memesona, maka Mupus Braen adalah puncak merias diri, puncak keindahan, yang hanya dilakukan sekali seumur hidup: saat menikah.
Pengantin di panggung malam itu mengenakan pakaian merah dan hitam, merah melambangkan keberanian menghadapi hidup rumah tangga. Hitam adalah doa agar langgeng sampai maut memisahkan. Di atas kepala, bunga melati putih disematkan sebagai lambang kesucian dan keharuman. Mahkota emas menambah agung, seolah cinta yang mereka bawa harus tegak berdiri di hadapan waktu.
Saya tiba-tiba menyadari: riasan itu bukan kosmetik semata. Ia adalah kitab yang dibaca dengan mata. Merah, hitam, putih, emas, setiap warna adalah doa, setiap perhiasan adalah nasihat. Bahwa cinta tidak cukup hanya dengan rasa. Ia butuh keberanian, ia butuh doa, ia butuh kesucian, ia butuh keagungan, dan saya berkhayal jika saya yang jadi mempelainya.
Betapa kontras dengan cinta-cinta yang sering saya lihat di luar panggung: cinta yang tergesa, cinta yang tumbuh cepat lalu layu seketika, cinta yang berakhir bahkan sebelum sempat dirayakan. Mupus Braen mengajarkan hal sebaliknya, cinta adalah puncak yang dicapai lewat kesabaran.
Ada aturan yang unik: Mupus Braen hanya untuk anak bungsu, saya bertanya dalam hati, mengapa demikian? Mengapa hanya bungsu yang berhak? Mengapa yang lain tidak?. Saya tidak menemukan jawabannya malam itu. Namun, semakin saya renungi, semakin saya merasa ada filosofi cinta di balik aturan itu. Anak bungsu adalah penutup sebuah garis, akhir dari sebuah generasi. Mungkin itu simbol bahwa cinta sejati adalah yang terakhir, yang mengikat sepenuhnya, yang bukan lagi permainan atau percobaan.
Apakah itu berarti setiap orang memang ditakdirkan jatuh cinta berkali-kali, hingga menemukan yang terakhir? Saya tidak tahu. Tetapi saya tahu, di usia tertentu, cinta berhenti menjadi bunga liar yang bisa tumbuh di mana saja. Ia berubah menjadi pohon besar. Ia menuntut akar yang dalam. Ia memerlukan tanah subur, air, dan kesabaran yang panjang, selain riasan, tradisi ini juga membawa ubarampe: bantal, guling, tikar, ayam, telur, kelapa, kampil putih. Semua disertai doa. Semua membawa makna.
Saya suka membayangkan cinta dengan cara yang sama. Cinta membutuhkan bantal untuk tempat beristirahat, guling untuk sandaran, tikar untuk alas kebersamaan, ayam dan telur untuk keberlangsungan hidup, kelapa untuk keteguhan, kampil putih untuk kesederhanaan, tidak ada cinta yang bertahan hanya dengan ciuman dan janji. Ia membutuhkan ubarampe sehari-hari: kesabaran, pengertian, pengorbanan, tawa, dan doa. Banyak orang ingin cinta yang indah, tetapi enggan mengumpulkan ubarampe itu. Padahal tanpa ubarampe, cinta hanya akan menjadi pesta semalam, lalu padam ketika lampu dipadamkan.
Saya teringat sebuah doa Nabi Muhammad saw. dalam pernikahan: “Semoga Allah memberkahimu, memberkahi atasmu, dan menghimpun kalian berdua dalam kebaikan.” Doa sederhana, tapi menyeluruh. Dan doa itu, barangkali, adalah ubarampe paling penting. Tuhan memahami semua bahasa, termasuk bahasa simbol. Tuhan tahu doa manusia meski tidak diucapkan dengan lisan. Doa bisa hadir lewat tanda, lewat isyarat, lewat ubarampe. Di tanah Osing, setelah akad nikah, doa sering diiringi shalawat dan kembar mayang: dua rangkaian kembang yang penuh tanda. Ada iembang jambe, ada bunga yang biasanya dipakai di pemakaman, ada buah-buahan. Semua itu doa yang disamarkan, harapan agar pernikahan tidak akan dipisahkan kecuali oleh kematian, lalu disatukan kembali di alam kelanggengan.
Malam itu, ketika pertunjukan usai dan tepuk tangan bergema, saya berdiri diam, saya tahu saya tidak baru saja menonton tari-tarian, saya sedang menonton tafsir cinta.
Cinta, rupanya, adalah tradisi. Ia bukan sekadar perasaan dua orang, melainkan doa leluhur, nasihat orang tua, dan harapan anak-anak yang belum lahir. Cinta adalah ritual kecil sehari-hari: menunggu dengan sabar, menjemput dengan ikhlas, memberi kabar dengan jujur, menahan amarah dengan rendah hati, dan memaafkan dengan tulus. Mupus Braen mengajarkan itu dengan bahasa yang indah. Bahwa cinta adalah daun muda yang rapuh, tapi juga indah. Bahwa cinta adalah merah keberanian, hitam doa panjang, putih kesucian, emas keagungan. Bahwa cinta membutuhkan ubarampe sederhana: sabar, doa, tawa, dan pengorbanan.
Saya pulang dari festival itu dengan langkah pelan di angin malam menyapa wajah saya, seperti tangan yang lembut. Di jalan, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang yang turun ke bumi. Saya merasa ditemani sesuatu yang tidak bisa saya lihat, tapi bisa saya rasakan. Saya tahu, cinta bukan lagi sekadar perasaan. Ia adalah upacara. Ia adalah doa yang harus dipelihara setiap hari.
Dan di Banyuwangi, doa itu diwariskan lewat Mupus Braen Blambangan.