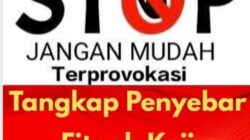Oleh: Syafaat – Ketua Lentera Sastra Banyuwangi
Ada kalimat yang membuat saya diam cukup lama hari ini. Kalimat itu muncul dari sebuah portal berita daring penyedia jasa penyembelihan hewan qurban dan aqiqah. Saya menemukannya di grup WhatsApp. Tulisannya mungkin dimaksudkan untuk memberikan informasi, tapi justru terasa seperti menabrak pelan-pelan satu lapisan kenyataan. Isinya begini kira-kira “Miris, saking jarangnya terima daging kurban, masyarakat osing Banyuwangi awetkan daging hingga bertahun-tahun”. Kalimat itu yang tampaknya ditulis dengan niat baik yakni mengajak untuk berkurban, yang dalam kalimat berikutnya tertulis “Di Iduladha ini, jangan biarkan daging kurban kamu menumpuk tak termakan. Yuk, bagikan juga kepada mereka yang jarang atau bahkan belum pernah merasakan nikmatnya dengan tunaikan kurbanmu” ini seperti menyodorkan kunci palsu untuk membuka lemari yang bahkan tak mereka kenali isinya. Di sinilah letak masalahnya: tidak semua yang kita lihat bisa langsung dinarasikan. Meskipun postingan tersebut akhirnya di take down, namun terlanjur membuat banyak orang kecewa karena narasi yang dibuat tidak disertai dengan data yang valid.
Narasi bukan sekadar catatan visual atau pengumpulan data sepintas. Narasi adalah kerja rasa. Dan rasa lahir dari perjumpaan yang cukup. Perjumpaan itu bisa berupa masa kecil yang dihabiskan di dapur, obrolan di atas lincak bambu saat sore, atau ikut nimbrung ketika nenek menyisihkan daging kurban ke tampah sebelum diproses jadi bekamal. Kalau tidak pernah hadir dalam peristiwa itu, jangan terburu-buru membubuhkan simpulan. Karena yang lahir dari simpulan prematur bukan pengetahuan, melainkan kesimpangsiuran makna.
Banyuwangi bukan sekadar kota di ujung timur Pulau Jawa. Ia adalah peta rasa yang dijaga laut dan ladang. Dan laut di sana tidak pernah pelit. Ia lemparkan ikan sepuas-puasnya. Masyarakat nelayan pun, yang tahu laut tak kenal musim panen seperti padi, belajar cara menyimpan ikan. Di situlah lahir metode seperti dipindang, kresek, dan Gerang, bukan karena kelaparan, tapi karena laut memberi terlalu banyak. Mereka belajar menyimpan bukan karena kekurangan, melainkan karena keberlimpahan.
Begitu pula dengan daging. Makanan di Banyuwangi tidak pernah bercita rasa sederhana. Di balik setiap kepulan uap rujak soto atau kuah pecel rawon, tersimpan riwayat panjang tentang bagaimana masyarakat Osing merayakan rasa dan bertahan hidup. Mereka tidak membiarkan tubuh kekurangan tenaga. Ikan laut mudah didapat. Daging menthok yang diolah menjadi geseng adalah hasil dari keakraban mereka dengan halaman belakang. Ayam kesrut bukan sekadar lauk. Ia adalah pernyataan rasa: asam dan pedas yang kuat, seperti keberanian mereka menghadapi hidup.
Saya pernah berpikir bahwa masyarakat agraris lebih banyak makan sayur. Tapi di Banyuwangi, bahkan pecel pun bisa diracik dengan kuah rawon yang gurih dan hitam legam. Protein hewani bukan kemewahan dari supermarket, tapi bagian dari keseharian. Tidak ada orang Osing yang repot-repot mengukur kandungan gizi. Tapi tubuh mereka kuat karena kebiasaan turun-temurun menyantap apa yang tersedia dari tanah dan lautnya sendiri.
Saya mencoba menghubungi seorang teman di Glagah Agung, sebuah desa tenang dekat hutan Grajagan. Saya tanya, berapa hewan kurban tahun ini? Ia jawab, “Alhamdulillah, di Masjid An-Nur depan rumah ada 37 ekor sapi, hampir sama seperti tahun lalu.” Ia menyebut angka itu dengan pelan, tapi dalam suaranya saya menangkap lebih dari sekadar jumlah: ada rasa syukur yang hening, juga semacam perasaan bahwa hidup, betapapun dunia berubah, di kampungnya tetap berjalan dengan irama yang dikenalnya sejak kecil. Seperti embun pagi yang selalu hadir di rerumputan belakang rumahnya. Belum lagi di beberapa masjid di desa tersebut yang rata-rata juga berkurban sapi yang jumlahnya lebih dari satu.
Kalau daging begitu melimpah, bagaimana mungkin masyarakat Osing disebut jarang makan daging?. Dalam dunia yang kelebihan, manusia belajar menyimpan. Dalam dunia yang kekurangan, manusia belajar bertahan. Dua hal ini tidak boleh ditukar tempat dalam narasi. Begitu juga saat hari raya kurban tiba di Banyuwangi. Di kampung-kampung Osing, hampir setiap masjid dan musala menyembelih hewan kurban. Seekor sapi dibagi menjadi ratusan bungkus. Kadang satu rumah mendapat lebih dari satu bungkus. Daging itu terlalu banyak untuk dimasak dalam satu hari. Tidak semua rumah punya kulkas. Bahkan dulu, tidak ada sama sekali.
Maka orang belajar menyimpan dengan cara mereka sendiri. Daging dikeringkan, dibumbui, difermentasi. Hasil akhirnya disebut pegal, atau bekamal. Bukan karena lapar. Tapi karena tahu: makanan ini harus bertahan untuk hari esok Kang Pur dari Kemiren, yang sangat saya hormati dan kenal sebagai budayawan Osing tulen, sudah menulis di grup Dewan Kesenian Banyuwangi (DKB), “Iki wong durung weruh kesusu gawe narasi.” Artinya, “Orang ini belum paham, tapi sudah buru-buru membuat narasi.” Kalimat itu keras tapi benar. Proses membuat bekamal tidak sesingkat menulis berita. Bekamal itu seni.
Daging dipotong rapi. Dibumbui. Dimasukkan ke dalam usus. Seperti sosis? Mungkin. Tapi ini sosis leluhur. Disimpan dalam pendek, toples, atau cukup digantung di udara terbuka. Fermentasi perlahan terjadi. Rasa menguat. Umur simpan bertambah. Ini bukan sekadar olahan, melainkan perayaan atas waktu dan keberlimpahan. Tidak ada satu pun proses yang tergesa-gesa.
Salah satu anggota grup lain, pewaris rasa Banyuwangi, menulis dengan cara yang membuat waktu seakan berjalan lebih lambat. Kalimat-kalimatnya pendek, jujur, tak tergesa, seolah ia tahu betul bahwa yang enak tak perlu dijelaskan dengan tergopoh. “Bekamal iku khusus isi daging,” tulisnya. Selebihnya adalah irama tanah: jeroan, ketimus, di besel-beselaken, di lebokaken pendek, diserungkup, dipepe. Ada sesuatu yang sunyi tapi tetap hangat dalam logat itu, seperti suara kompor minyak tanah yang menyala kecil menjelang subuh, atau bau pekat dari dapur tua yang masih menyimpan banyak cerita.
Kalimat itu bukan sekadar penjelasan tentang makanan. Ia seperti pintu kecil menuju masa lalu yang tak diawetkan dengan kamera, tapi dengan rasa dan bau dan tangan-tangan yang tahu cara membungkus musim. Ketika orang lain sibuk mendefinisikan fermentasi dalam suhu dan derajat, orang ini hanya menulis: “di rageni terus di fermentasi.” Lalu selesai. Tak ada angka, tak ada teori. Hanya kepercayaan lama yang berjalan dari mulut ke mulut, dari tangan ke tangan, dari pagi ke pagi berikutnya. Dan dalam dunia yang terlalu cepat ini, kadang-kadang, yang seperti itulah yang justru paling bertahan.
Kalimat itu seperti aroma dapur yang keluar dari sela papan rumah tua. Ada bumbu. Ada waktu. Ada kesabaran. Tak ada yang tergesa. Dan kita, yang hidup di era serba cepat, sering lupa bahwa tidak semua hal bisa dipahami dalam dua jam kunjungan atau dua paragraf riset Google. Narasi yang baik, seperti bekamal, perlu waktu. Tak bisa dibuat hanya karena deadline. Ia lahir dari pemahaman, bukan prasangka. Ia harus tahan lama. Karena itu ia perlu fermentasi. Perlu pengeringan. Perlu dijemur bersama matahari pagi dan dibungkus dengan kejujuran.
Dan orang Banyuwangi, yang hidupnya ditakar oleh angin laut dan debu ladang, tahu satu hal yang tak pernah diajarkan di sekolah-sekolah kota: bahwa yang baik itu tidak pernah terburu-buru. Seperti bekamal yang diserungkup dalam diam, dibiarkan bicara dengan waktu dan udara, agar ia tak hanya jadi makanan, tapi kenangan. Seperti musim yang tak bisa dipaksa datang lebih awal, mereka percaya pada kesabaran, pada perlahan yang tidak malas, pada lambat yang tidak lemah. Di antara bau tanah yang basah oleh embun dan suara kentongan subuh yang masih dikerjakan tangan-tangan renta, mereka belajar bahwa kekuatan selalu tumbuh diam-diam, dan yang lekas mekar terlalu sering cepat gugur.
Mereka tak terlalu butuh kalimat panjang atau penjelasan dari luar kota. Cukup sepotong logat, cukup bunyi “teber arane ketimus” yang hanya bisa diterjemahkan oleh ingatan. Di sana, dalam kalimat-kalimat sederhana yang beraroma garam dan tembakau, mereka menyimpan dunia yang tak bisa dijual atau diunggah. Yang layak diceritakan, kata mereka, bukan yang selesai cepat. Tapi yang mengendap pelan-pelan dalam dada, menyisakan rasa yang tak mudah basi. Dan dari sanalah kita tahu: bahwa hidup yang benar tidak selalu harus gegas, tapi cukup jujur, cukup hangat, dan cukup untuk dikenang.